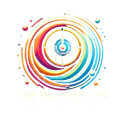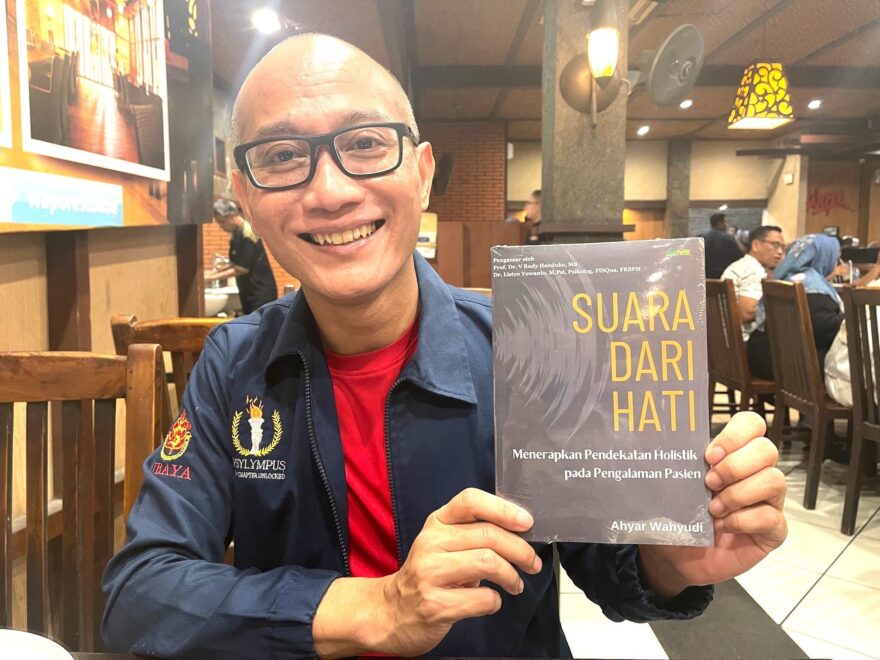Oleh. DR. H. Ahyar Wahyudi, S.Kep. Ns., M.Kep., CISHR, FISQua, FRSPH, FIHFAA (Reviewer Jurnal PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik)
Pertengahan Juli 2024, di sebuah desa yang tersembunyi di sela-sela dua gunung megah, Merapi dan Merbabu, tersimpan kisah-kisah kehidupan yang sunyi namun penuh makna. Desa ini, dikelilingi oleh pemandangan alam yang memukau, menyimpan rahasia-rahasia kecil yang jauh dari gemerlap kehidupan kota. Namun, di balik keindahan alamnya, ada kehidupan yang dijalani dengan penuh tantangan, diwarnai oleh kesulitan yang jarang tersentuh oleh bantuan dari luar.
Sahabatku, seorang psikolog yang datang dari Surabaya, mengunjungi desa ini dengan misi sederhana—untuk mendengarkan, untuk merasakan, dan untuk memberi sedikit harapan bagi mereka yang hidup dalam keterbatasan. Saat ia pertama kali menapakkan kaki di desa ini, ia disambut dengan pemandangan dua gunung yang menjulang tinggi, seolah menjadi penjaga setia desa yang terletak di lembah ini. Namun, di balik keheningan alam yang menyejukkan, sahabatku segera merasakan ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah kesunyian yang membungkus desa ini dengan rasa duka yang tak terlihat.
Di rumah-rumah sederhana yang berdiri di sepanjang jalan desa, hidup orang-orang yang telah melewati banyak badai kehidupan. Mereka adalah lansia-lansia yang menghabiskan sisa hidup mereka dalam kondisi yang serba kekurangan, baik secara fisik maupun ekonomi. Dalam setiap pertemuan, sahabatku menemukan cerita-cerita yang mengharukan—cerita tentang kesepian, kesakitan, dan harapan yang hampir padam.
Pak A, seorang lelaki tua berusia 72 tahun, adalah salah satu dari mereka. Dulu, Pak A dikenal sebagai petani yang tak pernah menyerah pada keadaan. Namun, satu kecelakaan kecil telah mengubah hidupnya secara drastis. Kakinya, yang dulu kuat menopang tubuhnya saat ia bekerja di ladang, kini tak lagi bisa digunakan untuk berjalan. Sebuah jatuh yang tampaknya sepele ternyata menimbulkan luka yang dalam pada tulangnya, luka yang tak terlihat dari luar namun terasa begitu nyata setiap kali ia mencoba bergerak. Di desa yang jauh dari akses layanan kesehatan memadai ini, Pak A tidak mendapatkan perawatan yang layak. Tak ada obat yang bisa meredakan nyerinya, dan tak ada suntikan yang bisa meringankan bebannya. Ketika rasa sakit itu datang, yang bisa ia lakukan hanyalah menahan atau berharap ada tetangga yang mau mengurut kakinya dengan harapan rasa sakit itu sedikit berkurang. Kruk bekas yang diberikan oleh anaknya menjadi satu-satunya alat bantu yang membuatnya bisa berpindah tempat, meski dengan langkah yang tertatih-tatih. Kehidupan Pak A kini tak lagi seperti dulu. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah, duduk di beranda, menatap dua gunung yang menjulang di kejauhan dengan mata yang penuh penyesalan dan keputusasaan.
Di rumah lain, hidup Ibu X, seorang perempuan tua yang hidup dalam kesendirian. Ia telah kehilangan banyak dalam hidupnya, terutama kehadiran anak-anaknya yang kini tinggal jauh darinya. Kesepian yang mencekam adalah teman setianya, sementara harapan untuk berkumpul kembali dengan anak-anaknya semakin hari semakin tipis. Setiap hari, Ibu X menggantungkan hidupnya pada belas kasih tetangga yang sesekali memberinya makanan. Ia tahu bahwa mereka juga hidup dalam kemiskinan, tetapi kebaikan hati mereka memberinya kekuatan untuk bertahan. Dalam diam, ia sering teringat akan masa-masa ketika keluarganya masih lengkap, ketika rumah ini dipenuhi oleh canda tawa anak-anaknya. Namun, kini yang tersisa hanyalah kenangan dan keheningan yang seakan memperpanjang kesedihannya. Dalam keputusasaan, Ibu X sering kali mencoba mencari anak-anaknya. Ia berjalan sejauh yang bisa ia tempuh, meski tanpa biaya dan tanpa kepastian akan bertemu. Perjalanan itu sering kali berakhir dengan kekecewaan, dan ia kembali ke rumahnya dengan hati yang semakin berat.
Ibu Y, seorang perempuan berusia 84 tahun, juga menjalani nasib yang tak kalah memilukan. Setelah menjalani operasi ginjal yang seharusnya membawa harapan baru, Ibu Y harus menerima kenyataan pahit bahwa matanya kini tak lagi bisa melihat dunia. Dunia yang dulu penuh warna kini berubah menjadi kegelapan yang menakutkan. Namun, yang lebih menyakitkan bagi Ibu Y adalah kondisi anaknya. Anaknya, yang seharusnya menjadi tumpuan harapannya di usia senjanya, ternyata mengidap skizofrenia. Gangguan jiwa berat ini membuat anaknya tidak hanya kehilangan pegangan pada kenyataan, tetapi juga mengancam keselamatan orang-orang di sekitarnya, termasuk ibunya sendiri. Dalam keadaan yang serba sulit ini, Ibu Y hanya bisa pasrah, menyerahkan nasibnya pada waktu dan berharap ada keajaiban yang bisa mengubah segalanya.
Di sebuah rumah sederhana lainnya, Ibu W menjalani hidupnya yang penuh dengan keterbatasan sejak kecil. Ia tumbuh tanpa kehadiran ibu, dan sebatang kara setelah ibunya meninggal dunia. Kehidupan yang keras dihabiskan tanpa pendamping, tanpa keluarga yang bisa menjadi tempat bersandar. Ia jatuh dan mengalami kelainan pada kakinya, membuatnya tak bisa bergerak seperti orang lain. Desa yang mengenalnya sebagai “perempuan tua yang malang” akhirnya membantunya dengan membangunkan sebuah rumah petak kayu, sebuah tempat berteduh dari panas dan hujan, namun tak bisa mengusir dingin di hatinya. Fungsi adaptif Ibu W sudah sangat terganggu. Ia hanya akan makan dan minum jika ada tetangga yang datang memberinya. Tetangga-tetangga yang sebenarnya juga hidup dalam keterbatasan, namun tetap menunjukkan kebaikan hati yang luar biasa.
Ibu A, yang meskipun usianya telah mencapai 102 tahun, masih memiliki semangat hidup yang tinggi. Sayangnya, kebutaannya sejak kecil membuat hidupnya penuh dengan tantangan. Ibu A merasa tak memiliki apa-apa, tak bisa memberikan apa-apa, dan itu membuatnya merasa bersalah. Setiap kali seseorang datang menemuinya, ia merasa dirinya menjadi beban, merepotkan orang lain yang sebenarnya memiliki kehidupan mereka sendiri untuk diurus. Perasaan tak berdaya ini, meski sering kali disembunyikan di balik senyumnya, sebenarnya menghancurkan semangatnya sedikit demi sedikit.
Di ujung desa, ada Ibu F yang nasibnya tak kalah menyedihkan. Masalah tenggorokan yang dialaminya membuatnya tidak bisa berbicara dengan jelas, dan kondisi ini membuatnya mendapat stigma dari masyarakat. Mereka yang tidak mengerti, yang tidak mencoba memahami, malah menjulukinya “gila.” Stigma ini, yang begitu kejam, membuat Ibu F semakin terpuruk. Ia merasa diasingkan dari kehidupan sosial, seakan-akan tidak ada tempat baginya di dunia ini. Ketika orang lain hidup dengan stigma yang mereka terima dari masyarakat, Ibu F hidup dengan stigma yang ia terima dari dirinya sendiri—perasaan bahwa ia tidak lagi layak untuk menjadi bagian dari masyarakat yang lebih luas.
Ketika sahabatku menyusuri jalan-jalan kecil di desa ini, di sela-sela dua gunung yang megah, ia menyadari bahwa desa ini adalah cerminan dari kehidupan itu sendiri—sebuah perjalanan yang penuh dengan lika-liku, dengan kesedihan dan kebahagiaan yang datang silih berganti. Ia mendapati bahwa di tengah segala keterbatasan ini, masih ada seberkas cahaya, sebuah harapan yang meski redup, masih mampu menyinari hati mereka yang hidup dalam kegelapan.
Sahabatku mendengarkan cerita-cerita mereka dengan penuh perhatian. Ia tahu bahwa yang mereka butuhkan bukan hanya nasihat atau solusi instan, tetapi lebih dari itu, mereka membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan, yang mau memahami, dan yang mau memberikan sedikit perhatian dalam kehidupan mereka yang sepi. Dalam setiap pertemuan, ia berusaha untuk membangun kembali rasa percaya diri dan martabat yang mungkin telah lama hilang dari diri mereka.
Dalam teorinya, Bronfenbrenner menyatakan bahwa individu dipengaruhi oleh berbagai lapisan lingkungan di sekitarnya, mulai dari keluarga hingga masyarakat luas【Bronfenbrenner, 1979】. Dalam konteks desa ini, lapisan-lapisan tersebut sering kali tidak mendukung kesejahteraan para lansia. Kurangnya dukungan sosial, akses layanan kesehatan yang minim, dan stigma sosial yang kuat membuat mereka merasa terisolasi dan tidak berharga.
Namun, sahabatku percaya bahwa dari keterbatasan ini, masih ada jalan keluar. Ia mulai mengidentifikasi langkah-langkah kecil yang bisa diambil untuk membantu mereka. Ia bekerja sama dengan komunitas lokal untuk mencari cara agar para lansia ini mendapatkan perawatan kesehatan yang lebih baik. Ia juga berusaha membangun jaringan dukungan sosial yang lebih kuat di desa tersebut, dengan melibatkan tetangga dan keluarga yang mungkin sudah lama tidak terhubung dengan mereka. Ini adalah upaya kecil, tetapi ia percaya bahwa dari langkah kecil inilah perubahan besar bisa dimulai.
Sahabatku juga berusaha mengatasi stigma yang melekat pada beberapa dari mereka. Menurut teori stigma Goffman, individu yang diberi label negatif oleh masyarakat sering kali menerima label tersebut sebagai identitas mereka sendiri, yang pada gilirannya memperkuat marginalisasi mereka【Goffman, 1963】. Sahabatku mencoba untuk mengubah pandangan ini, baik dari sisi masyarakat maupun individu yang terkena stigma. Ia berbicara kepada mereka tentang pentingnya menerima diri mereka sendiri, bahwa kondisi fisik atau mental mereka tidak mengurangi nilai mereka sebagai manusia.
Desa ini, dengan segala kesulitan dan tantangannya, sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi tempat yang lebih baik bagi para lansia. Sahabatku melihat kebaikan hati tetangga-tetangga mereka yang meski hidup dalam keterbatasan, tetap bersedia membantu. Ia percaya bahwa dengan sedikit bantuan dan dorongan, desa ini bisa menjadi contoh bagaimana komunitas yang peduli bisa membuat perbedaan besar dalam hidup seseorang.
Di sela-sela dua gunung yang megah, Merapi dan Merbabu, kisah-kisah ini menjadi pengingat bahwa di balik keindahan alam, ada manusia-manusia yang berjuang dalam kesunyian. Mereka mungkin tidak terdengar suaranya, tetapi mereka ada, dan mereka layak mendapatkan perhatian kita. Dalam setiap langkah sahabatku, ia membawa serta harapan bahwa perubahan, meski kecil, bisa terjadi. Ia meninggalkan desa itu dengan perasaan campur aduk—senang karena bisa membantu, tetapi juga sedih karena tahu masih banyak yang harus dilakukan.
Saat ia menatap kedua gunung yang menjulang tinggi itu, sahabatku menyadari bahwa hidup ini, seperti gunung-gunung tersebut, penuh dengan lika-liku dan tantangan. Namun, setiap langkah kecil yang kita ambil, setiap kebaikan yang kita berikan, membawa kita lebih dekat ke tujuan kita—menciptakan dunia yang lebih adil, lebih peduli, dan lebih penuh kasih sayang.
Hidup ini, seperti yang sering dikatakan oleh para filsuf, adalah perjalanan yang tidak selalu mudah. Di sepanjang jalan, kita akan menemui banyak rintangan, banyak kesedihan, dan mungkin juga banyak keputusasaan. Namun, di balik setiap tantangan, selalu ada kesempatan untuk tumbuh, untuk belajar, dan untuk menemukan kekuatan yang tersembunyi di dalam diri kita. Seperti pepatah lama mengatakan, “Setiap badai pasti berlalu,” dan setelah hujan, akan selalu ada pelangi yang menanti kita.
Dalam kesedihan yang melingkupi desa di lembah antara Merapi dan Merbabu ini, ada pelajaran penting yang bisa kita ambil—bahwa dalam setiap langkah yang kita ambil, kita memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan, untuk membawa sedikit cahaya di tengah kegelapan, dan untuk memberikan harapan kepada mereka yang mungkin sudah lama kehilangan harapannya. Dan itulah makna sejati dari kemanusiaan—untuk saling mendukung, untuk saling membantu, dan untuk tidak pernah menyerah dalam menghadapi segala tantangan yang datang.