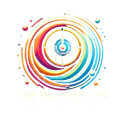Ilustrasi Kasus: Melintasi Lorong Gelap Identitas
Dalam lorong gelap sebuah kota yang gemerlap, seorang remaja bernama Andini melangkah ragu-ragu menuju cermin. Di balik tatapannya yang kosong, tersembunyi pertempuran batin yang tak terlihat, antara keinginan untuk menjadi diri sendiri dan tekanan sosial yang tak henti-hentinya memaksanya untuk menyesuaikan diri. Andini lahir sebagai laki-laki, tetapi dalam dirinya, dia merasa sebagai perempuan. Keluarganya adalah benteng konservatisme yang teguh, dan lingkungan sekitarnya mengharapkan dia untuk tumbuh menjadi sosok yang memenuhi standar maskulinitas yang telah lama tertanam. Di sekolah, ejekan dan intimidasi menjadi makanan sehari-hari, menambah luka pada jiwa yang rapuh. Namun, di dunia maya, Andini menemukan kebebasan. Di sanalah ia bertemu dengan komunitas yang merangkulnya, yang menerima identitasnya tanpa syarat. Di dunia maya, ia bisa menjadi Andini yang sesungguhnya—perempuan yang selama ini terkurung dalam tubuh yang tidak ia kenali sebagai miliknya.
Namun, kebebasan ini tidak datang tanpa harga. Andini mulai merasakan ketegangan yang semakin membesar antara identitas maya dan realitas hidupnya. Dalam perjalanan mencari jati diri, Andini terseret ke dalam pusaran konflik batin yang mendalam—antara memenuhi ekspektasi masyarakat dan memenuhi kebutuhannya sendiri untuk diterima apa adanya. Dalam kebingungan ini, Andini akhirnya memutuskan untuk keluar, untuk menunjukkan kepada dunia siapa dia sebenarnya. Tetapi, keputusan ini membawa serangkaian konsekuensi yang tak terduga—penolakan dari keluarga, pengucilan dari komunitas, dan akhirnya, keterasingan dari dirinya sendiri. Dalam upaya untuk menemukan kebebasan, Andini justru menemukan dirinya terperangkap dalam labirin identitas yang tak berujung.
Kesombongan sebagai Dosa Arketipal
Kesombongan adalah akar dari semua dosa, demikianlah yang diyakini Agustinus dari Hippo, teolog besar yang pemikirannya tetap relevan hingga kini. Dalam karya monumental City of God, Agustinus menelusuri jejak kesombongan yang membawa kehancuran bagi manusia dan kota duniawi. Kesombongan adalah bentuk penolakan terhadap Tuhan, sebuah usaha manusia untuk mengangkat dirinya di atas tatanan ilahi. Ini adalah dosa yang memutus hubungan antara manusia dan penciptanya, menjadikan manusia sebagai tuan atas dirinya sendiri, dan pada akhirnya, menjadi budak dari hasrat dan keinginan yang tak terkendali.
Dalam Pride Month, kita dapat melihat manifestasi dari kesombongan kolektif ini. Perayaan ini, yang seharusnya menjadi momen untuk merayakan kebebasan dan identitas, sering kali berubah menjadi arena di mana manusia memproklamirkan kebebasan mereka dari tatanan moral yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Seperti yang Agustinus katakan, kesombongan ini bukanlah kebebasan sejati, melainkan perbudakan dalam bentuk baru. Manusia menjadi budak dari identitas yang mereka ciptakan sendiri, terperangkap dalam siklus tanpa akhir untuk mencari validasi dan pengakuan dari dunia di sekitar mereka.
Dalam pandangan Agustinus, kesombongan adalah dosa arketipal yang menjadi akar dari semua pemberontakan manusia terhadap Tuhan. Ia melihat bahwa menempatkan dirinya di atas tatanan ilahi, hasilnya selalu sama—kehancuran moral, spiritual, dan sosial. Pride Month, dalam kacamata Agustinus, mungkin dilihat sebagai cerminan dari libido dominandi, hasrat untuk mendominasi, yang justru mendominasi manusia itu sendiri. Ini adalah hasrat yang mendorong manusia untuk menolak kebenaran yang telah ditetapkan oleh Tuhan dan berusaha menciptakan realitas baru yang sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Namun, sebagaimana yang diingatkan oleh Agustinus, setiap usaha untuk menentang tatanan ilahi akan selalu berujung pada kehancuran, bukan kebebasan.
Performativity dan Identitas
Judith Butler, seorang filsuf kontemporer yang karyanya banyak dikutip dalam diskusi tentang gender dan identitas, memperkenalkan konsep performativity, di mana identitas gender dipahami sebagai sesuatu yang “dilakukan” melalui tindakan berulang yang diakui oleh masyarakat. Butler berargumen bahwa identitas gender bukanlah esensi yang melekat pada individu, melainkan sebuah peran yang dimainkan dalam panggung sosial, yang terus-menerus dikonstruksi dan dikonfirmasi melalui tindakan dan perilaku sehari-hari.
Konsep ini menantang pandangan esensialis tradisional tentang identitas, termasuk pandangan Agustinus yang memandang identitas sebagai sesuatu yang diberikan oleh Tuhan dan harus diterima dengan kerendahan hati. Dalam perspektif Agustinus, upaya untuk mendefinisikan ulang identitas sesuai dengan kehendak manusia adalah bentuk kesombongan yang paling mendasar. Ini adalah usaha untuk menggantikan Tuhan sebagai sumber dari identitas, dan pada akhirnya, ini adalah tindakan yang akan membawa kehancuran bagi individu dan masyarakat.
Namun, dalam masyarakat modern, konsep performativity telah menjadi dasar dari banyak diskusi tentang identitas gender, terutama dalam konteks LGBTQ+. Pride Month menjadi momen di mana individu menegaskan identitas mereka yang dibangun di atas konsep ini, menantang norma-norma tradisional yang dianggap membatasi kebebasan mereka. Tetapi, seperti yang dikemukakan oleh Agustinus, upaya ini tidak akan menghasilkan kebebasan sejati, melainkan perbudakan yang baru—perbudakan terhadap kebutuhan untuk terus-menerus mempertahankan dan mengafirmasi identitas yang rapuh ini di hadapan masyarakat.
Simbolisme dan Makna dalam Pride Month
Ensiklopedia Britannica mencatat bahwa Pride Month diperingati setiap bulan Juni untuk mengenang peristiwa di Stonewall Inn pada tahun 1969, yang menjadi tonggak sejarah bagi gerakan hak-hak LGBTQ+. Seiring berjalannya waktu, berbagai simbol seperti bendera pelangi dan lambda telah menjadi identik dengan gerakan ini. Simbol-simbol ini, meskipun sederhana dalam desainnya, membawa makna yang mendalam dan menjadi alat bagi komunitas LGBTQ+ untuk menegaskan keberadaan dan identitas mereka di tengah masyarakat yang sering kali tidak menerima mereka.
Namun, simbolisme ini juga mengandung paradoks yang mendalam. Di satu sisi, simbol-simbol ini dimaksudkan untuk merayakan keragaman dan kebebasan. Di sisi lain, mereka juga mencerminkan upaya untuk mendefinisikan ulang identitas manusia di luar tatanan moral yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dalam perspektif Agustinus, simbol-simbol ini mungkin dilihat sebagai lambang dari kota duniawi yang dipenuhi oleh kesombongan dan hasrat untuk mendominasi. Kota duniawi ini, atau civitas terrena, adalah tempat di mana manusia berusaha untuk menghapus batasan-batasan moral dan menciptakan tatanan baru yang didasarkan pada keinginan dan hasrat mereka sendiri, bukan pada kebenaran ilahi.
Krisis Identitas
Krisis identitas yang dialami oleh banyak individu dalam masyarakat modern, terutama dalam konteks LGBTQ+, adalah cerminan dari krisis nilai yang lebih luas. Ensiklopedia Britannica mencatat bahwa semakin banyak individu, terutama kaum muda, yang mendefinisikan ulang identitas gender mereka sejak usia dini. Fenomena ini, meskipun sering kali dilihat sebagai kemajuan dalam hal kebebasan individu, juga menimbulkan berbagai tantangan bagi keluarga, institusi pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan.
Agustinus, dengan pemikiran teologisnya yang mendalam, akan melihat krisis ini sebagai tanda dari pemberontakan manusia terhadap Tuhan. Ketika manusia mencoba untuk mendefinisikan ulang identitas mereka di luar tatanan ilahi, hasilnya adalah kebingungan dan ketidakpuasan yang mendalam. Identitas yang dibangun di atas dasar pemberontakan ini tidak akan pernah membawa kedamaian atau kebahagiaan sejati, melainkan hanya menciptakan ketegangan dan konflik yang tak berkesudahan dalam masyarakat.
Dalam krisis identitas ini, kita juga melihat bagaimana masyarakat kehilangan fondasi moral yang kuat. Ketika identitas menjadi sesuatu yang relatif dan dapat diubah sesuai dengan kehendak individu, masyarakat kehilangan pegangan pada nilai-nilai yang dulu menjadi penopang utama dari tatanan sosial. Ini bukan hanya masalah individual, tetapi juga masalah kolektif yang mengancam integritas dan keberlanjutan dari masyarakat itu sendiri.
Respon terhadap Tantangan Moral dalam Kota Manusia
Agustinus menawarkan solusi yang mendasar untuk menghadapi tantangan moral yang dihadapi oleh kota duniawi. Pertama, ia menekankan pentingnya kerendahan hati dalam menerima kenyataan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Hanya dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, manusia bisa menemukan kebahagiaan sejati yang tidak didasarkan pada ilusi atau kesombongan, tetapi pada kebenaran ilahi yang tidak berubah.
Kedua, Agustinus mengajak kita untuk menolak agama sipil modern yang merusak, seperti yang diwujudkan dalam Pride Month. Ini bukan berarti menolak orang-orangnya, tetapi menolak nilai-nilai yang merusak yang mereka anut. Kita harus berani menyuarakan kebenaran, meskipun itu mungkin tidak populer, dan mengundang orang-orang untuk meninggalkan ilusi mereka dan menemukan makna sejati dalam hidup yang diatur oleh tatanan ilahi.
Ketiga, Agustinus mengingatkan kita untuk selalu mengundang orang-orang yang berada di bawah pengaruh agama sipil modern ini untuk menemukan kebebasan sejati dalam Tuhan. Kebebasan sejati bukanlah kebebasan untuk melakukan apa saja yang kita inginkan, tetapi kebebasan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini adalah kebebasan yang membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati, karena didasarkan pada kebenaran yang tak tergoyahkan.
Penutup
Sebagaimana sebuah kapal yang terlunta-lunta di tengah badai, demikian pula manusia yang mencoba mendefinisikan ulang identitas dan kebenaran mereka di luar tatanan ilahi. Kapal itu mungkin terlihat bebas, bergerak ke segala arah tanpa kendali, tetapi tanpa arah yang jelas, ia akhirnya akan tenggelam dalam kekacauan laut yang tak bertepi. Dalam City of God, Agustinus mengingatkan kita bahwa hanya dengan berpegang teguh pada kebenaran ilahi, kita bisa menemukan jalan yang aman menuju kebahagiaan sejati.
Indonesia, dengan segala keragaman dan tantangannya, bisa belajar banyak dari pemikiran Agustinus. Di tengah arus modernisasi yang sering kali membawa krisis identitas dan nilai, kita perlu kembali kepada prinsip-prinsip moral yang telah terbukti kebenarannya sepanjang sejarah. Hanya dengan demikian, kita bisa membangun masyarakat yang lebih kuat, bersatu, dan penuh kebahagiaan sejati. Sebagaimana sebuah pohon yang kokoh berakar dalam tanah yang subur, demikian pula masyarakat yang berdiri di atas fondasi moral yang kuat akan mampu bertahan dan berkembang, meskipun badai perubahan terus menerjang.
Referensi:
- Butler, J. (1990). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Routledge.
- Smith, J. K. A. (2019). On the Road with Saint Augustine: A Real-World Spirituality for Restless Hearts. Brazos Press.
- Wood, J. R. (2024). “Sacred time for the city of man.” WORLD Opinions. Diakses dari https://worldopinions.com/sacred-time-for-the-city-of-man
- Encyclopedia Britannica. (n.d.). Pride Month. Encyclopedia Britannica. Diakses dari https://www.britannica.com/topic/Pride-Month