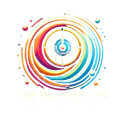Oleh. DR. H. Ahyar Wahyudi, S.Kep. Ns., M.Kep., CISHR, FISQua, FRSPH, FIHFAA (PP LAFKI)
Budaya keselamatan pasien tidak bisa dianggap sebagai sekadar formalitas atau syarat administratif menjelang survei akreditasi. Di Indonesia, praktik pengukuran budaya keselamatan pasien yang terbatas pada momen tertentu sering kali mencerminkan pemahaman yang belum matang tentang pentingnya integrasi keselamatan dalam setiap aktivitas organisasi kesehatan. Sejatinya, budaya keselamatan yang kuat terbentuk dari perilaku kolektif yang konsisten, di mana setiap individu dalam organisasi memiliki peran penting dalam memastikan lingkungan perawatan yang aman dan bebas dari kesalahan yang dapat membahayakan pasien.
Dalam kerangka teori Edgar Schein, budaya organisasi dibangun dari nilai-nilai dan keyakinan yang mengakar, yang kemudian tercermin dalam perilaku sehari-hari anggota organisasi. Budaya keselamatan pasien, dalam hal ini, bukan hanya sekadar kebijakan atau prosedur yang diikuti ketika waktu survei akreditasi mendekat, tetapi harus menjadi bagian tak terpisahkan dari tindakan setiap individu di fasilitas kesehatan. James Reason menegaskan bahwa perilaku individu dan kelompok dalam organisasi adalah pilar utama yang menopang keselamatan. Ketika perilaku ini didukung oleh sistem yang mendorong praktik keselamatan, maka terciptalah budaya keselamatan yang tangguh dan berkelanjutan.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak fasilitas kesehatan di Indonesia hanya berfokus pada pengukuran budaya keselamatan ketika menghadapi akreditasi. Hal ini menciptakan budaya keselamatan yang bersifat sementara dan tidak berkelanjutan. Pengukuran yang hanya dilakukan secara sporadis atau insidental cenderung memunculkan budaya semu, di mana keselamatan menjadi prioritas hanya ketika ada tekanan eksternal. Pendekatan semacam ini bertolak belakang dengan esensi budaya keselamatan yang sejati, di mana keselamatan harus menjadi inti dari setiap tindakan, bukan sekadar tuntutan birokrasi.
Dalam perspektif perilaku organisasi, pengukuran budaya keselamatan yang dilakukan secara berkelanjutan setiap 12 atau 24 bulan akan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai sejauh mana perilaku keselamatan telah terinternalisasi dalam rutinitas harian. Guldenmund menggarisbawahi bahwa budaya keselamatan yang kuat hanya dapat terwujud jika perilaku proaktif terkait keselamatan telah menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari. Lebih lanjut, Reason menjelaskan bahwa pengukuran yang berkesinambungan memungkinkan organisasi untuk memonitor dan mengevaluasi secara sistematis bagaimana perilaku keselamatan berkembang dari waktu ke waktu, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.
Guna mewujudkan budaya keselamatan yang solid, pengukuran tidak boleh berhenti pada angka atau data semata. Hasil dari pengukuran ini harus menjadi dasar bagi pelatihan yang berfokus pada perubahan perilaku. Sebagaimana dijelaskan oleh Kirkpatrick, pelatihan yang efektif bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga mampu mengubah cara kerja individu. Feedback yang diberikan setelah pengukuran harus bersifat konstruktif, mendorong staf untuk terus memperbaiki perilaku mereka. Bandura menekankan bahwa reinforcement positif melalui umpan balik yang terstruktur dapat memperkuat perilaku yang diinginkan, sehingga budaya keselamatan yang diharapkan dapat tumbuh dan mengakar lebih dalam.
Di samping itu, pengukuran yang berkelanjutan juga membuka ruang bagi inovasi dalam praktik keselamatan. Kaplan dan Norton menegaskan bahwa dalam lingkungan yang dinamis, pengukuran yang teratur tidak hanya membantu dalam pemantauan, tetapi juga mendorong organisasi untuk terus mencari solusi baru yang dapat meningkatkan kualitas keselamatan pasien. Inovasi-inovasi ini, pada akhirnya, tidak hanya akan meningkatkan keselamatan tetapi juga kualitas pelayanan secara keseluruhan.
Namun, untuk mencapai semua itu, perubahan paradigma dalam pendekatan terhadap pengukuran budaya keselamatan di Indonesia sangat diperlukan. Saat ini, banyak organisasi kesehatan masih terjebak dalam pola pikir yang menganggap pengukuran ini sebagai formalitas menjelang akreditasi. Kurangnya pemahaman akan pentingnya pengukuran yang berkelanjutan, ditambah dengan keterbatasan sumber daya, menjadi penghalang utama dalam menciptakan budaya keselamatan yang berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan komitmen kuat dari semua pihak, baik di tingkat manajemen maupun staf, untuk menjadikan pengukuran budaya keselamatan sebagai bagian dari siklus perbaikan berkelanjutan dalam organisasi.
Kesimpulannya, pengukuran budaya keselamatan pasien di Indonesia harus mengalami transformasi dari sekadar formalitas menjadi alat yang efektif dalam membentuk perilaku proaktif yang mendukung keselamatan. Dengan menerapkan pengukuran yang berkelanjutan, memberikan feedback yang konstruktif, dan mendorong inovasi, organisasi kesehatan dapat membangun budaya keselamatan yang kuat, di mana keselamatan pasien bukan hanya sebuah konsep, tetapi menjadi napas dari setiap tindakan yang diambil.