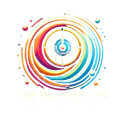Oleh. DR. H. Ahyar Wahyudi, S.Kep. Ns., M.Kep., CISHR, FISQua, FRSPH, FIHFAA (Alumni UMY Yogyakarta)
Pulang ke kotamu, Jogja, adalah seperti menyusuri jalan kenangan yang telah dilapisi oleh debu waktu, namun tetap bersinar dengan kehangatan yang tidak pudar. Dulu, dua puluh tiga tahun yang lalu, aku berjalan menyusuri jalan dari timur ke barat, dari kampus menuju rumah kos yang telah menjadi saksi bisu perjalanan hidupku. Setiap sudut kota ini, setiap deretan bangunan tua yang kokoh berdiri, mengingatkan aku akan mimpi-mimpi yang pernah kuanyam di bawah langit Jogja yang selalu penuh bintang. Jogja, dengan segala keajaibannya, adalah tempat di mana aku menemukan diri, menggali makna hidup, dan merajut masa depan.
Namun, kini, ketika aku akan kembali menyusuri jalanan itu, akan ada sesuatu yang berbeda. Ada bayang-bayang yang menghantui, seakan-akan kenangan masa lalu yang indah telah bercampur dengan kabut kesedihan yang mendalam. Di kota yang selalu kuanggap sebagai rumah kedua ini, aku mendengar berita tentang tingginya angka prevalensi skizofrenia, sebuah gangguan jiwa berat yang merenggut kehidupan dan kebahagiaan banyak orang. Berita ini bagaikan angin dingin yang menusuk tulang, mengingatkan kita bahwa di balik keindahan Jogja, tersembunyi derita yang tak kasat mata.
Sebuah Kenyataan yang Menyentuh Hati
Skizofrenia bukanlah kata yang asing bagi mereka yang pernah mendalami ilmu psikologi atau kesehatan jiwa, namun bagi banyak orang, skizofrenia tetap menjadi misteri yang menakutkan. Ini adalah gangguan yang memisahkan seseorang dari kenyataan, membuat mereka terperangkap dalam dunia yang tidak dipahami oleh orang lain. Di Yogyakarta, kota yang selama ini dikenal dengan kekayaan budaya dan keramahtamahannya, skizofrenia justru menemukan tempatnya, berkembang dan menyebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, DIY mencatat prevalensi tertinggi untuk gangguan jiwa psikosis/skizofrenia di Indonesia, dengan angka yang mencapai 9,3 persen.
Bagaimana mungkin di kota yang penuh dengan kedamaian dan keindahan ini, begitu banyak orang terjebak dalam dunia yang dipenuhi dengan halusinasi, delusi, dan kekacauan mental? Apakah ini adalah harga yang harus dibayar atas perkembangan zaman, atas tekanan hidup yang semakin berat, atau mungkin ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang telah lama terabaikan oleh masyarakat kita?
Mengenang Jalanan Jogja: Dulu dan Sekarang
Aku masih ingat dengan jelas bagaimana aku menyusuri jalanan Jogja yang sepi di malam hari, hanya ditemani suara jangkrik dan angin yang berdesir lembut di antara pepohonan. Ada kedamaian yang tak tergantikan di kota ini, kedamaian yang memberi ruang bagi setiap individu untuk merenung, untuk mencari jati diri. Namun kini, di tengah-tengah keramaian kota, di antara gemerlap lampu dan hiruk-pikuk kehidupan modern, ada mereka yang terjebak dalam kesunyian yang tak dapat dijangkau oleh orang lain. Mereka adalah jiwa-jiwa yang terasing, yang terperangkap dalam penjara pikiran mereka sendiri, tanpa ada jalan keluar yang jelas.
Dulu, ketika aku masih kuliah di Jogja, aku sering melihat orang-orang yang duduk termenung di pinggir jalan, seakan-akan mereka sedang berbicara dengan seseorang yang tak kasat mata. Saat itu, aku tidak mengerti apa yang mereka alami, tidak pernah terpikirkan olehku bahwa mungkin mereka adalah salah satu dari banyak orang yang menderita skizofrenia. Kini, setelah puluhan tahun berlalu, aku menyadari bahwa mereka adalah bagian dari cerita yang lebih besar, cerita tentang bagaimana gangguan mental seperti skizofrenia telah menyusup ke dalam kehidupan masyarakat kita, tanpa ada yang benar-benar menyadari betapa seriusnya masalah ini.
Skizofrenia: Antara Harapan dan Realitas
Skizofrenia, dalam banyak hal, adalah sebuah paradoks. Di satu sisi, ini adalah gangguan yang menghancurkan, yang merenggut kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan normal, untuk berhubungan dengan orang lain, dan untuk berfungsi di masyarakat. Namun di sisi lain, skizofrenia juga merupakan sebuah misteri yang belum sepenuhnya terpecahkan oleh ilmu pengetahuan. Ada begitu banyak teori tentang penyebab dan mekanisme yang mendasari gangguan ini, namun tidak ada yang benar-benar bisa menjelaskan dengan pasti mengapa seseorang bisa terkena skizofrenia.
Salah satu teori yang paling diterima secara luas adalah teori ketidakseimbangan kimia di otak, di mana skizofrenia diduga disebabkan oleh ketidakseimbangan neurotransmiter seperti dopamin dan glutamat. Ketidakseimbangan ini menyebabkan gangguan pada sistem saraf, yang pada gilirannya mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku. Namun, meskipun teori ini didukung oleh banyak penelitian, masih banyak yang tidak diketahui tentang bagaimana dan mengapa ketidakseimbangan ini terjadi. Apakah itu karena faktor genetik, lingkungan, atau kombinasi keduanya? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang masih belum memiliki jawaban pasti (Lahargo, 2024).
Selain faktor biokimia, ada juga teori yang menekankan pentingnya faktor sosial dan psikologis dalam perkembangan skizofrenia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa stres berat, trauma, dan tekanan sosial dapat memicu timbulnya gejala skizofrenia, terutama pada individu yang memiliki predisposisi genetik terhadap gangguan ini. Di Jogja, dengan segala perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir, tidaklah mengherankan jika tekanan hidup menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya prevalensi skizofrenia di kota ini (Nasruddin, 2024).
Menghadapi Tantangan dengan Empati
Dalam menghadapi realitas yang begitu pahit ini, kita tidak bisa hanya berpangku tangan dan membiarkan mereka yang menderita skizofrenia terjebak dalam dunia mereka sendiri. Sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas, kita memiliki tanggung jawab moral untuk membantu mereka, untuk memberikan dukungan yang mereka butuhkan, dan untuk memastikan bahwa mereka tidak merasa sendirian dalam perjuangan mereka. Ini adalah panggilan bagi kita semua untuk menjadi lebih peduli, lebih memahami, dan lebih empatik terhadap mereka yang hidup dengan gangguan mental.
Empati bukan hanya tentang merasa iba atau kasihan, tetapi tentang mencoba memahami apa yang orang lain rasakan dan mengalami, dan berusaha untuk membuat hidup mereka sedikit lebih baik. Dalam konteks skizofrenia, empati berarti mengakui bahwa gangguan ini adalah sesuatu yang nyata, bahwa itu bukanlah pilihan atau kelemahan, tetapi sebuah kondisi medis yang membutuhkan perawatan dan dukungan yang tepat. Empati juga berarti berbicara secara terbuka tentang masalah kesehatan mental, menghilangkan stigma, dan menciptakan lingkungan di mana orang merasa aman untuk mencari bantuan tanpa takut dihakimi.
Langkah Menuju Masa Depan yang Lebih Baik
Untuk benar-benar membantu mereka yang hidup dengan skizofrenia, kita perlu mengambil langkah-langkah konkret yang melibatkan semua aspek masyarakat. Pertama-tama, perlu ada peningkatan dalam akses terhadap layanan kesehatan mental yang berkualitas. Ini termasuk diagnosis dini, pengobatan yang tepat, dan dukungan berkelanjutan untuk penderita skizofrenia dan keluarganya. Pemerintah dan lembaga kesehatan perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap orang yang membutuhkan perawatan dapat mengaksesnya tanpa kesulitan finansial atau geografis (Kemenkes RI, 2024).
Selain itu, edukasi adalah kunci untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap skizofrenia. Kampanye kesadaran tentang kesehatan mental harus dilakukan secara luas, melibatkan sekolah, tempat kerja, dan komunitas, untuk memastikan bahwa semua orang memahami apa itu skizofrenia, bagaimana mengenali gejalanya, dan bagaimana memberikan dukungan kepada mereka yang terpengaruh. Ini bukan hanya tugas para profesional kesehatan, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai individu yang peduli terhadap kesejahteraan sesama (Corrigan, 2024).
Di Jogja, kita juga perlu mempertimbangkan pendekatan berbasis komunitas dalam menangani skizofrenia. Program-program seperti Rumah Berdaya di Denpasar bisa menjadi model yang diadopsi di kota ini, dengan memberikan rehabilitasi sosial dan dukungan komunitas bagi mereka yang hidup dengan skizofrenia. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengurangi beban rumah sakit jiwa, tetapi juga memberikan dukungan yang lebih personal dan berkelanjutan bagi penderita, memungkinkan mereka untuk tetap terhubung dengan masyarakat dan tidak merasa terasing (Rumah Berdaya, 2024).
Penutup
Ketika aku kembali ke Jogja, aku tidak hanya menemukan kota yang telah banyak berubah, tetapi juga realitas yang lebih mendalam tentang bagaimana kehidupan telah berkembang di sini. Di balik keindahan dan kedamaian kota ini, ada cerita tentang penderitaan yang tak terlihat, tentang jiwa-jiwa yang terperangkap dalam kegelapan skizofrenia. Namun, di tengah-tengah semua ini, aku juga menemukan harapan. Harapan bahwa dengan empati, pemahaman, dan tindakan nyata, kita bisa membantu mereka yang menderita skizofrenia untuk menemukan jalan keluar dari kegelapan, untuk kembali merasakan cahaya dan kehangatan yang pernah kita nikmati di Jogja yang indah ini.
Dengan segala upaya yang kita lakukan, semoga suatu hari nanti, Jogja tidak lagi dikenal sebagai kota dengan prevalensi skizofrenia tertinggi, tetapi sebagai kota yang penuh dengan cinta, empati, dan kepedulian terhadap sesama.
Referensi
- Corrigan, P. W. (2024). The Stigma of Mental Illness: Empowering Strategies for Individuals and Communities. Oxford University Press.
- Kementerian Kesehatan RI. (2024). Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Lahargo, K. (2024). Skizofrenia: Tantangan dan Harapan. Psikologika.
- Nasruddin, M. (2024). Stigma dan Mitos dalam Penanganan Gangguan Jiwa di Indonesia. Pustaka Pelajar.
- Rumah Berdaya. (2024). Rehabilitasi Sosial Berbasis Komunitas untuk Penderita Skizofrenia. Retrieved from rumahberdaya.org.